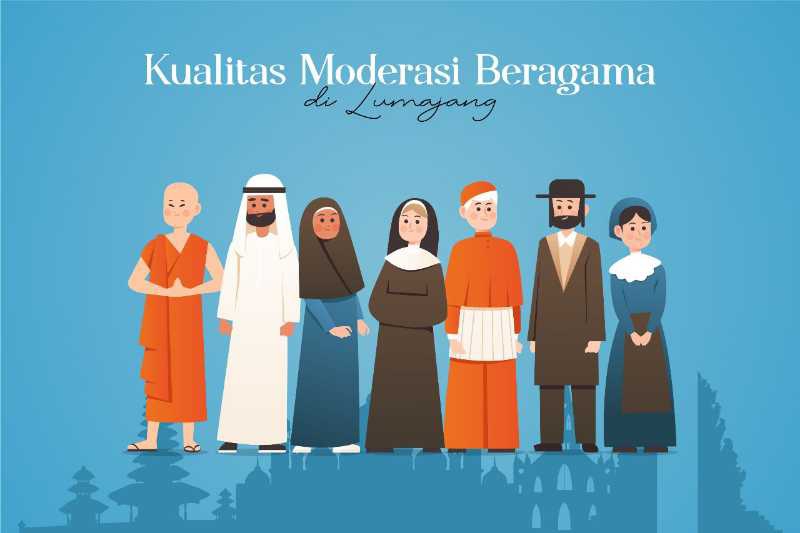Penolakan warga terhadap pendirian Gereja di Tempeh Tengah Kabupaten Lumajang menampar wajah kebebasan beragama kita yang telah digaransi oleh konstitusi. Penolakan itu juga menggambarkan wajah “bopeng” toleransi dan moderasi beragama kita yang masih jauh panggang dari api.
Dalam berbagai banyak kasus, perbedaan umat beragama menjadikan berbagai gesekan bahkan hingga berbentuk ekstrem yang menimbulkan kesalahpahaman, kesalahan tafsir hingga problematika dari akar rumput sosial kemasyarakatan. Banyaknya ormas dan aliran yang berkembang di sosial masyarakat Indonesia, tidak jarang menjadikan potensi munculnya konflik dan gesekan yang terjadi. Tentu hal ini bukanlah isapan jempol belaka. Seperti kasus kekerasan pembakaran rumah ibadah yang terjadi di Pronojiwo Kabupaten Lumajang merupakan fakta yang terjadi di kalangan masyarakat.
Hal ini tidak lain adalah bentuk kesalahpahaman masyarakat tentang isu-isu keagamaan yang berkembang. Belum lagi problem yang hangat saat ini diperbincangkan yakni tentang penolakan warga terhadap pendirian Gereja di Tempeh Tengah Kabupaten Lumajang. Begitupun kontroversi yang terjadi di masyarakat tentang pembangunan rumah ibadah baru yang dianggap mengancam Keberadaan umat beragama tertentu.
Kasus-kasus diatas, jika boleh disimpulkan, terjadi karena masyarakat kita gagal melakukan rekonsiliasi dan resolusi yang elegan dan bermartabat atas berbagai perbedaan keyakinan keberagamaan. Akibatnya, muncullah serangkaian kesalahpahaman di kalangan masyarakat yang berujung pada gesekan dan konflik sosial kemasyarakatan. Bagi masyarakat tertentu yang telah dibekali dengan local wisdom atau pranata sosial tentang mekanisme manajemen konflik dan perbedaan, perbedaan penafsiran keagamaan seekstrem apapun barangkali tidak perlu di khawatirkan. Namun, bagi masyarakat yang tidak memiliki kekenyalan sosiologis akibat absennya pranata sosial-budaya dimaksud, sekecil apapun perbedaan tafsir keagamaan, mudah akan diprovokasi dan dikonversi ke arah konflik keras yang destruktif. Di sinilah pentingnya kita memiliki integritas moderasi beragama yang tangguh dan kokoh secara sosiologis sehingga masyarakat kita tidak mudah untuk diprovokasi ke arah konflik sosial keagamaan.
Pejabat publik sebagai representatif dari negara, sudah selayaknya melindungi kebebasan beragama warganya. Apapun alasannya, penolakan pendirian rumah ibadah tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan Pancasila, dan konstitusi kita UUD 1945. Dalam pasal 28E Ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Pasal 29 Ayat (2) juga menjelaskan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Selain itu, penolakan terhadap pendirian rumah ibadah juga sangat mencederai hak dasar beragama.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengelompokkan hak beragama sebagai hak setiap orang yang tidak bisa ditunda (non-derogable rights) oleh dan dengan alasan apa pun, baik dalam kondisi damai maupun perang. Di Indonesia, konsep kebebasan beragama sebagai non-derogable rights juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Pasal 4) yang menjamin hak beragama sebagai perwujudan HAM yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapapun.
Kualitas Moderasi Beragama
Lebih jauh, penolakan pendirian rumah ibadah di Lumajang juga mencederai nilai-nilai moderasi beragama yang sudah dicanangkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023. Penolakan tersebut memukul telak toleransi beragama sebagai salah satu indikator moderasi beragama. Ironisnya, para penolak menggunakan argumentasi kearifan lokal untuk menolak pendirian rumah ibadah. Padahal, toleransi dan kearifan lokal merupakan dua dari empat indikator moderasi beragama yang tidak boleh bertentangan satu sama lain (selain indikator kebangsaan dan antikekerasan).
Barangkali yang perlu disadari oleh para penolak adalah efek domino dari penolakan mereka terhadap nasib umat Islam di daerah lain yang mayoritas non-Islam, terutama di luar Jawa. Harus diakui, perlakuan mayoritas Muslim terhadap kaum minoritas penganut Kristiani sering kali menimbulkan efek domino yang mengganggu harmoni dan toleransi beragama di daerah lain. Sikap penolakan tersebut tak jarang menyulut aksi pembalasan terhadap kaum Muslim ketika mereka hendak mendirikan masjid di daerah minoritas Islam di luar Jawa. Pola relasi antarumat beragama yang tidak sehat ini sudah saatnya dihentikan.
Fenomena lain yang perlu dicermati terkait kualitas moderasi beragama kita adalah penendangan sesajen di Lumajang beberapa saat lalu. Penendangan sesajen oleh seorang oknum relawan saat meletusnya gunung Semeru membuat banyak pihak merasa geram karena dianggap telah melukai tradisi lokal yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Fenomena penendangan sesajen ini sempat viral di media social dan dilaporkan secara berulang-ulang di sejumlah kanal televisi. Karena dianggap telah melukai tradisi lokal, tak ayal banyak pihak menghendaki agar yang bersangkutan diadili di muka hukum.
Fenomena penendangan sesajen mengindikasikan model beragama yang tidak ramah budaya. Hal semacam ini terjadi akibat munculnya visi beragama yang purifikasionis atau berorientasi pada pemurnian agama dari elemen-elemen budaya lokal. Kepenganutan terhadap model keberagamaan purifikasionis menjadi fakta sosiologis yang banyak kita jumpai di kalangan masyarakat kita. Mereka memiliki keyakinan bahwa model beragama yang benar haruslah murni dari berbagai macam ketercampuran unsur-unsur budaya lokal yang dianggap tidak Islami. Mereka menganggap syirik terhadap praktik keberagamaan yang terlah tercampur dengan budaya lokal. Oleh karena itu, mereka sangat mengutuk dan membenci praktik-praktik keberagamaan yang telah bercampur dengan budaya lokal seperti slametan, larung sasajen, sedekah bumi, dan lain sebagainya.
Dalam konteks ini, kelompok purifikasionis jugalah yang sering melontarkan kritik dan ketidaksetujuan mereka atas gagasan moderasi beragama. Moderasi beragama dianggap program pendangkalan akidah yang didesain oleh para musuh Islam dalam rangka merongrong dan meruntuhkan agama ini. Tak jarang mereka bahkan menuduh program moderasi beragama sebagai proyek non-Muslim, Yahudi, dan liberalis yang diinjeksi kepada tubuh umat Islam untuk melemahkan militansi keberagamaan mereka. Secara konseptual, mereka menganggap program moderasi tidak memiliki pijakan tekstual-normatif yang kokoh dan tidak menunjukkan kejelasan posisi teologis yang kuat. Oleh karena itu, mereka mengkritiknya sebagai konsep “la-wala” (tidak ke kanan ataupun tidak ke kiri; tidak ke Barat maupun ke Timur).
Militansi Moderasi Beragama
Bagi kita umat Islam di Indonesia, konsep moderasi beragama menjadi kekuatan dan modalitas sosial yang membuat wajah keberagamaan kita menjadi sejuk, damai, indah, toleran dan rahmatan lil alamin. Modalitas sosial-keberagamaan semacam ini sudah barang tentu menjadi anugerah yang tidak ternilai harganya di tengah berkecamuknya konflik kekerasan yang melanda umat Muslim di belahan dunia (baca: beberapa negara mayoritas Muslim di Timur Tengah). Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mensyukuri anugerah ini dengan merayakan dan mempraktikkan moderasi beragama secara konsisten, sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
Terlebih lagi, konsep moderasi beragama telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Artinya, sudah menjadi program nasional yang harus diimplementasikan. Sebagai bagian dari tanggungjawab kenegaraan, maka Kementerian Agama menjadi institusi garda terdepan dalam mengamankan dan menjalankan program moderasi beragama di seluruh jenjang kelembagaan. Tidak boleh ada standar ganda dalam menyikapi dan memahami program moderasi beragama kecuali hanya satu kata, “laksanakan!”.
Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Kementerian Agama RI, moderasi beragama dicirikan oleh aspek-aspek berikut ini;
1). Anti-kekerasan dalam menjalankan misi dakwah keagamaan;
2). Prinsip toleransi dalam menyikapi perbedaan;
3). Memiliki wawasan kebangsaan yang kukuh (nasionalisme);
4). Akomodatif terhadap tradisi lokal (Kemenag RI, 2019).
Keempat aspek ini adalah “standar minimal” bagi seseorang untuk disebut moderat. Ada juga syarat-syarat lain yang bisa ditambahkan di sini seperti berpikir rasional dan terbukanya pintu ijtihad. Dengan demikian, siapapun umat Muslim yang tidak memiliki salah satu beberapa aspek di atas, berarti dia masih belum bisa disebut moderat.
Perlu juga dipahami bersama bahwa ketidakjelasan pendirian keagamaan sebagaimana dituding oleh kelompok non-moderat dapat dipatahkan dengan argumentasi normatif-teologis sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an: “dan yang demikian telah Kami jadikan kalian ummat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia..” (QS. Al-Baqarah: 143). Selain itu, paradigma moderasi beragama juga sejalan dengan sabda Nabi Muhammad Saw.; “sebaik-baik persoalan adalah yang (berada) di tengah-tengah”. Rasulullah Saw. juga bersabda: “tengah-tengah itu adil; kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah (terbaik)” (HR. Tirmidzi dan Ahmad). Dalil-dalil normatif semacam ini mestinya membuat kita umat Muslim semakin teguh, militan dan konsistensi dalam menyikapi dan melaksanakan konsep moderasi beragama.
Penulis: Akhmad Afnan Fajarudin,
Pengurus Cabang PMII Kabupaten Lumajang